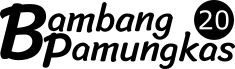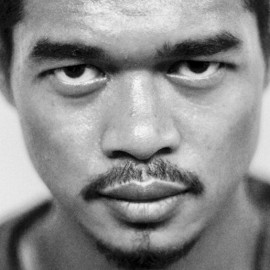“Aku memang tidak nampak seperti serdadu ataupun narapidana, akan tetapi pada kenyatannya aku adalah keduanya” - Emmeline Pankhurst.
Kalimat di atas, saya kutip dari salah satu pidato Emmeline Pankhurst yang sangat terkenal pada sekitar tahun 1913. Emmeline Pankhurst sendiri adalah pemimpin pergerakan perempuan di Inggris. Seorang perempuan yang dengan gigihnya memperjuangkan persamaan hak politik, bagi setiap perempuan Inggris. Dia pun harus rela keluar masuk penjara demi mewujudkan cita-citanya, yaitu untuk memberikan hak politik yang sama, bagi setiap wanita di Inggris Raya pada masa itu.
Ketika saya membaca pidato tersebut, seketika saya teringat dengan diri saya sendiri. Walaupun dalam konteks dan skala yang tentu sangat jauh berbeda, pada suatu ketika, saya juga pernah merasa berada dalam situasi dimana saya adalah seorang serdadu, sekaligus seorang narapidana.
Beginilah ceritanya:
Sebagai pesepakbola yang bermain untuk tim nasional, Saya atau kami lebih tepatnya, tentu banyak menghabiskan waktu di luar kota atau bahkan di luar negeri. Berbeda dengan ketika kita berada di klub, di tim nasional jadwal kami boleh dikatakan sangat ketat. Semua pemain harus bermalam di asrama (hotel) baik di Jakarta, atau di kota mana pun kami berada. Sehingga secara otomatis, kami tidak banyak memiliki waktu untuk bertemu dengan keluarga.
Bagi kami yang kebetulan tinggal di Jakarta atau kota tempat tim nasional tengah melakukan pemusatan latihan, maka kami berkesempatan bertemu keluarga, jika mereka datang berkunjung di waktu siang. Itu pun waktunya terbatas, karena kami harus istirahat untuk berlatih kembali di sore harinya. Bagi mereka yang keluarganya tinggal di luar kota tentu lebih sulit, karena mereka hanya berkomunikasi melalui telefon.
Apalagi jika kami harus melakukan lawatan atau pemusatan latihan ke luar negeri, yang terkadang bisa memakan waktu hingga 2 minggu, atau bahkan 1 bulan. Hal tersebut, sedikit banyak tentu mengganggu psikologis kami, terutama bagi yang sudah berkeluarga.
Seperti beberapa hari lalu saat kami berada di Oman. Sore itu, teman sekamar saya, Ponaryo Astaman terlihat sangat gelisah. Beberapa kali dia berbicara dengan istrinya melalui telepon. Dari mimik wajahnya nampak topiknya cukuplah serius. Singkat cerita, ternyata anak Ponaryo sedang demam tinggi di Jakarta.
Sebagai seorang ayah tentu sangat wajar jika dia gelisah, akan tetapi apa yang dia bisa perbuat saat ini? Jarak yang sangat jauh, membuat dia hanya bisa memantau kondisi anaknya melalui telepon. Mungkin lain cerita jika saat anaknya demam tinggi, dia sedang berada di rumah, atau di tempat yang memungkinkan untuk dia pulang ke rumah. Setidaknya, secara psikologis keberadaan seorang ayah akan mampu menjadi obat kepada buah hatinya.
Cerita yang lain datang dari Firman Utina. Pada suatu siang di Myanmar ketika saya, Aliyudin, Charis, dan Ismed sedang bermain domino di kamar saya, tiba-tiba Firman masuk dan bekata, “Sialan, anak gue ngga mau ngomong sama gue sekarang”, “Loh kenapa Man?” sahut Ismed, “Iya, katanya papa tukang bohong, katanya besok pulang tapi kok ngga pulang-pulang, mau nangis gue dengernya”, jelas Firman ketika itu.
Setali tiga uang dengan diri saya. Dua hari lalu, sepulang lawatan bersama tim nasional selama 2 minggu di Oman, saya pun mengalami kejadian yang kurang lebih sama. Sesaat setelah mendarat di Jakarta, kami diberi waktu 24 jam untuk bertemu dengan keluarga, karena 5 hari kemudian kami akan berhadapan dengan Australia di Jakarta.
Waktu yang singkat itu betul-betul Kami manfaatkan dengan baik. Para pemain yang keluarganya berada di luar Jakarta, pun sengaja menerbangkan keluarganya ke Jakarta. Sedang bagi pemain yang keluarganya di Jakarta seperti Saya, kami pun pulang ke rumah. Ternyata 24 jam adalah waktu yang sangat singkat.
Keesokan harinya saya pun harus kembali bergabung ke tim nasional yang beradi di Hotel Sultan. Selama perjalanan, anak bungsu saya Syaura duduk di pangkuan saya. Keliatan sekali, jika dia tidak ingin lepas dari saya saat itu. Saat mobil mulai saya memasuki parkiran hotel, dan pada akhirnya berhenti, saya pun mulai memindahkan Syaura ke tangan Dewi.
Saat itu Syaura bertanya “Pipi mau kemana?”, saya pun menjawab “Pipi Gol dulu ya, nanti malam Pipi pulang ya”. Tanpa menjawab Syaura mulai memeluk istri saya, dan terlihat mulai tergenang air di matanya. Istri saya pun berkata, “Udah jalan aja, paling nangis sebentar”.
Dengan sedikit berat, saya pun mulai turun dari mobil. Kaca mobil pun dibuka dan sambil berdiri di pangkuan istri saya Syaura mulai melambaikan tangan walaupun terlihat dengan sedikit terpaksa. Mobil perlahan-lahan mulai berjalan dan Syaura pun masih melambaikan tangan dengan posisi badan sedikit menjulur keluar dari kaca pintu mobil.
Tiba-tiba dengan sedikit melompat Syaura berteriak “Pipi ngga boleh gol, pipi ngga boleh gol”. Jika saja saat itu istri saya tidak sigap, mungkin Syaura sudah terjatuh dari mobil. Melihat kejadian itu secara reflek saya mengejar mobil saya, dan memegang anak saya. Tanpa saya sadari mata saya pun berkaca-kaca, sambil memeluk Syaura saya berkata, “Iya, iya pipi ngga gol sayang,” dan Syaura pun menangis di pelukan saya.
Beberapa cerita tadi hanyalah sedikit ilustrasi dari beberapa hal yang terjadi di kehidupan kami, para pesepakbola tim nasional. Mungkin hal-hal semacam itu, tidak pernah terlintas di benak masyarakat. Mungkin masyarakat hanya melihat kami dari sisi-sisi glamour saja. Menjadi pemain tim nasional itu selalu terlihat eksklusif, bergelimang fasilitas, sehingga hidup terasa lebih mudah dan menyenangkan.
Saya tidak pernah menafikan akan hal tersebut. Akan tetapi di sisi lain, banyak juga kisah yang tidak banyak masyarakat ketahui tentang kami. Sisi-sisi sentimentil yang lebih tepat jika disebut sebagai pengorbanan kami sebagai seorang pesepakbola tim nasional. Oleh karena itu, jika pada suatu ketika, secara membabi buta kami dihujat dan dicaci-maki oleh masyarakat. Ada kalanya juga, terlintas perasaan untuk meninggalkan seragam tim nasional, dan hanya berkonsentrasi di klub masing-masing saja.
Akar Permasalahan
Di saat persepakbolaan negara-negara tetangga sudah mulai berlari, kita masih hanya sekadar berjalan kaki. Dibutuhkan komitmen dari seluruh komponen yang terkait dalam bidang ini untuk dapat mengejar para tetangga. Selama ini, kita hanya mencari kambing hitam dalam setiap kegagalan tim nasional. Tanpa mahu duduk bersama untuk mencari dan menganalisa akar permasalahan yang sebenarnya. Sehingga solusi terbaik untuk mengatasinya permasalahan sepak bola kita pun tidak pernah kita temukan.
Persepakbolaan kita yang tak kunjung membaik ini adalah kesalahan kita bersama. Kesalahan Bambang Pamungkas (mewakili seluruh pesepakbola di Indonesia). Kesalahan Benny Dollo (mewakili seluruh pelatih di negeri ini). Kesalahan Purwanto (mewakili seluruh wasit di negara ini). Kesalahan Nurdin Halid (mewakili seluruh jajaran pengurus sepak bola di republik ini). Dan tentu juga kesalahan kalian semua, seluruh suporter sepak bola di seluruh nusantara.
Saya setuju dengan komentar Om Benny (Dollo) pada suatu ketika, “Di Indonesia ini, setiap klub hanya mencari sebuah kemenangan (dengan segala macam cara), tanpa mahu meningkatkan kualitas individu mau pun permainan tim”. Mereka bangga hanya dengan memenangkan pertandingan, walau terkadang dengan cara yang tidak fair. Mereka bahkan tidak perduli dengan kualitas permainan tim mereka sendiri.
Masalah akan timbul ketika para pemain tersebut bergabung ke tim nasional. Pemain yang terbiasa dengan suasana Liga Indonesia yang tidak kondusif tersebut, akan sulit beradaptasi dengan iklim pertandingan internasional. Parahnya lagi, tim nasional kita ini sangat jarang untuk melakukan ujicoba internasional. Itu yang membuat tim nasional kita sering kali gagap, dalam menjalani partai-partai internasional.
Ini adalah masalah pokok yang terjadi dalam sepakbola kita. Iklim liga yang profesional, kondusif, dan kompetitif akan bermuara kepada tim nasional yang kuat. Begitulah kira-kira prinsip dasarnya. Dan tidak dapat dimungkiri, jika saat ini sepak bola kita tidak memiliki hal itu.
Satu hal lagi yang selama ini kita lupa, yaitu regenerasi pemain. Regenerasi pemain kita, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini terjadi, karena terlalu banyaknya regulasi pemain asing di Liga Indonesia. Hal tersebut dengan sendirinya mengurangi menit bermain para pemain lokal di posisi-posisi yang krusial sebut saja center back, playmaker, dan juga striker.
Tiga pemain asing, atau empat pemain asing (satu cadangan, dan hanya boleh masuk menggantikan sesama pemain asing) dalam setiap klub rasanya sudah cukup ideal. Bukan lima pemain asing dan semuanya boleh turun bermain seperti yang terjadi saat ini. Di saat negara-negara tetangga sudah mulai menggunakan pemain-pemain dengan rata-rata usia muda di tim nasional mereka, kita masih saja menggunakan tentara-tentara lama.
Bagaimana para pemain muda kita dapat berkembang, jika mereka tidak mendapat kesempatan bermain yang cukup di klub masing-masing. Hal-hal seperti ini yang luput dari radar para pengurus PSSI. Para pemain senior kita mungkin masih dapat dipergunakan, akan tetapi mereka juga perlu pelapis. Di samping untuk alasan regenerasi, hal tersebut juga akan berguna sebagai tekanan kepada para pemain senior. Agar mereka paham, jika setiap saat posisi mereka juga bisa tergeser.
Untuk para junior, mereka juga bisa mulai belajar mendapatkan atmosfer sebuah laga internasional, yang nantinya pasti akan sangat berguna saat mereka mengambil alih panggung utama tim nasional. Itu baru sebuah iklim yang kompetitif dan positif untuk kebaikan bersama.
Serdadu dan Narapidana
Mengapa saya ibaratkan diri kami seperti, Serdadu dan Narapidana ?
Serdadu, karena kami adalah tentara paling depan yang berjuang dan bertanggungjawab untuk membela nama bangsa dan negara melalui sepak bola. Walaupun dengan persenjataan yang sering kali minim (ekosistem kompetisi yang tidak profesional dan kondusif). Dan kemudian ketika kami gagal, masyarakat tidak akan pernah mau tahu, yang mereka tahu kami adalah para pesakitan perang yang pantas dan sudah semestinya untuk dicaci-maki, tanpa mau tahu titik permasalahan yang sebenarnya. Layaknya seorang narapidana yang diseret ke balik terali besi.
Bagi kami para pemain, konsekuensi tersebut tentu sudah kami pahami sejak lama. Akan tetapi bagi keluarga kami, hal tersebut terkadang sedikit sulit untuk diterima, dan tidak jarang menimbulkan rasa frustasi. Namun pada akhirnya kecintaan terhadap profesi, tanggung jawab, serta kebanggaan atas nama panggilan negara membuat kami selalu bertahan di garis depan untuk terus berjuang.
Apapun alasannya, saya sangat mengecam para pemain yang menghindar dari kewajiban membela tim nasional. Di negara yang sepak bolanya maju, para pemain rela melakukan apapun agar mendapatkan kesempatan bermain untuk negara mereka. Karena menjadi pemain tim nasional adalah puncak karir seorang pesepakbola. Sebuah kebanggan sekaligus tanggung jawab. Sedangkan di negara kita, kesadaran itu masih sangat lah kurang. Di mata saya mereka adalah para “Pengecut”.
Sebagai “Serdadu maupun Narapida” sejujurnya kami tidak pernah peduli. Apapun situasi dan kondisinya, di sini kami tetap bangga. Sebuah semboyan yang akan selalu kami ingat dan pegang teguh adalah:
“Bermainlah untuk dirimu, orang-orang yang kamu cintai (keluarga) dan lambang garuda di dadamu (rakyat Indonesia)”
“Garuda di dadaku, Garuda kebangganku”.
Salam,
Bambang Pamungkas