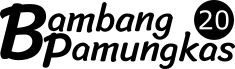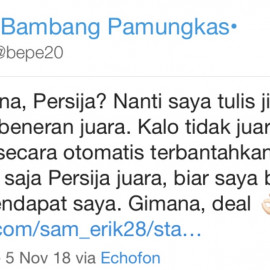SEPERTI yang pernah saya sampaikan di salah satu tulisan saya yang berjudul, “Tantanglah Dirimu Sendiri”. Jika salah satu alasan paling kuat, mengapa saya “tidak terlihat” dalam foto selebrasi tim Persija Jakarta saat menjadi juara liga Indonesia tahun 2001, adalah karena saya ingin memberikan kesempatan bagi para pemain senior untuk lebih dekat dengan piala.
Sebagai pencetak dua gol pada laga final yang juga dinobatkan sebagai pemain terbaik pada tahun itu, tentu sangat layak rasanya jika saya mendapatkan panggung malam itu. Namun sekali lagi, karena saya ingin menghormati senior-senior saya, maka saya memutuskan untuk berada di barisan belakang. Iya, karena bisa jadi piala itu adalah gelar terakhir dalam karir mereka, jadi biarkan mereka menikmatinya.
Sedang bagi saya, di mana ketika itu usia saya masih 21 tahun, saya berkeyakinan jika saya masih memiliki waktu yang panjang untuk dapat mengangkat piala-piala berikutnya bersama Persija Jakarta. Akan ada giliran bagi saya untuk berada di garis paling depan untuk menerima, dan kemudian mengangkat piala tersebut.
Agak arogan memang. Tapi itulah salah satu cara saya untuk memprovokasi dan menantang diri saya, untuk menjadi lebih baik.
Namun kenyataan memang tak selamanya seindah yang kita bayangkan. Tahun demi tahun setelah itu, gelar juara seperti enggan menyambangi kota Jakarta. Segala daya dan upaya rasanya sudah kami lakukan, namun selalu saja tidak cukup. Ada saja kerikil tajam yang membuat kami harus tergelincir di tikungan terakhir.
Ketika saya menyeberang ke Malaysia dan bermain untuk Selangor pada tahun 2005 hingga 2007, saya berhasil mempersembahkan gelar juara, beberapa malah. Sedang di waktu yang sama, Persija Jakarta tetap saja gagal menambah koleksi gelar. Walaupun ketika itu berhasil tampil di dua partai final, baik Liga Indonesia maupun Piala Indonesia.
Ketika saya memutuskan untuk kembali ke Persija, kejadian yang sama pun kembali berulang. Setiap tahunnya kami hanya menjadi tim besar yang menjadi favorit juara, namun gelar juaranya selalu saja menjadi milik tim lain.
Musim 2016, 2017, dan juga 2019 adalah musim terberat saya selama berseragam Persija Jakarta. Musim 2016 adalah yang paling parah, finis di peringkat 16 dengan hanya mengumpulkan 35 poin dari 34 pertandingan, jelas bukan gambaran dari tim sebesar Persija Jakarta. Musim 2017 juga tidak jauh beda, hujan dan badai datang silih berganti. Perubahan signifikan baru terjadi di pertengahan musim, hingga akhirnya kami berhasil finis di peringkat 4.
Spanduk kekecewaan pun bertebaran di mana-mana. Cacian, makian, si ini out, si itu out, atau permintaan pergantian pelatih terjadi hampir di sepanjang musim 2016 hingga pertangahan musim 2017. Nyanyian kekecewaan diikuti dengan bahasa tubuh yang kurang menyenangkan, menjadi pemandangan yang lumrah saat bus pemain keluar meninggalkan stadion. Tidak jarang kami pun dibuat emosi karenanya.
Saya masih ingat, ketika di akhir sebuah pertandingan kandang yang hasilnya kurang bagus, salah satu suporter yang berada di tribun VIP berteriak-teriak sambil mengacungkan sebuah piala. Ternyata piala tersebut terbuat dri plastik, dan di piala tersebut tertulis “Persija Kapan Juara?”.
Secara tersirat, tentu hal tersebut dapat diartikan jika sebagai sebuah tim, kami hanya layak meraih piala dari plastik dan bukan piala liga Indonesia (sungguhan). Ejekan yang merendahkan, sebuah akumulasi dari rasa kecewa yang sudah menggunung.
Hampir semua pemain marah ketika itu, termasuk juga saya. Namun di tengah suasana yang serba kurang nyaman, tiba-tiba sebuah suara lirih mengiang di telinga saya. Meminta saya untuk melihat peristiwa tersebut dari sisi yang lain, sisi yang lebih positif.
Kemudian saya pun coba menghampiri orang tersebut. Pihak keamanan menghalangi saya ketika itu, mereka berpikir jika saya berniat melakukan sesuatu yang kurang baik kepada suporter tersebut. Setelah sedikit memaksa dan meyakinkan jika saya tidak sedang berniat kurang baik, akhirnya saya pun diperbolehkan berjalan ke arah tribun VIP. Dengan pengawalan tentunya, untuk menjaga agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Saya pun menerima piala tersebut, dan mengucapkan terima kasih. Sayangnya saya tidak sempat menanyakan siapa nama orang tersebut. Tujuan awal saya adalah untuk meredakan situasi yang mulai memanas. Karena dengan menerima piala tersebut, maka pendukung kami akan merasa jika kritik mereka telah tersampaikan dengan baik, dan kondisi pun diharapkan menjadi lebih kondusif. Namun jauh lebih besar dari itu, saya ingin menjadikan piala plastik tersebut sebagai sebuah pengingat.
Di ruang ganti, beberapa pemain nampak kurang setuju dengan apa yang saya lakukan tadi. Walau tidak ada satu pun dari mereka yang menyampaikan secara langsung kepada saya, namun dari raut wajah mereka saya tahu, jika mereka tidak sepaham dengan saya.
Saya mengerti betul, jika setiap pemain sudah mengeluarkan kemampuan terbaik dan berusaha keras untuk memenangkan pertandingan. Memberikan piala plastik seperti itu jelas sebuah penghinaan. Saya bisa mengerti jika mereka sangat kesal, begitu pun saya. Tindakan saya tadi, mungkin dianggap terlalu lemah oleh sebagian pemain. Tidak apa-apa, mereka berhak berpikir demikian, toh pada akhirnya reaksi setiap orang dalam menyikapi sesuatu kan tidak harus sama.
Piala plastik itu pun saya bawa pulang. Sesampainya di rumah, piala tersebut saya letakkan di sebuah konsul yang berada di ruang keluarga saya. Berjajar di antara dua piala pemain terbaik saya. Kemudian lampu saya padamkan dan lilin pun saya nyalakan. Sejurus kemudian, saya mengabadikan piala plastik tersebut dengan ponsel saya.
Dewi yang memperhatikan dengan seksama sejak saya memasuki rumah, nampak memasang mimik heran. “Ngapain Cin?”, tanya dia kemudian. “Ngga papa”, jawab saya singkat. “Ngapain itu ditaruh di situ, ngga bagus lah Cin”, lanjut Dewi yang nampak keberatan. “Biarin aja Cin, jangan diapa-apain, biar disini saja”, jawab saya lagi. “Sampai kapan?”, lanjut Dewi yang masih heran dengan apa yang saya lakukan. “Sampai nanti aku yang mindahin sendiri”, jawab saya menutup pembicaraan.
Beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 26 Mei 2017, foto yang saya ambil malam itu pun saya posting di Instagram. Judul yang saya bubuhkan ketika itu adalah: “Rasa cinta memang dapat diwujudkan dengan cara yang begitu beragam”.
Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jika tujuan utama saya membawa piala itu pulang adalah sebagai pengingat. Pengingat jika ada sebuah kewajiban yang belum terbayar dengan lunas. Pengingat jika ada sebuah tantangan yang belum terselesaikan. Dan pengingat jika masih ada sebuah janji yang belum tertunaikan.
Peletakan piala plastik di atara dua piala pemain terbaik saya, juga bukan tanpa alasan. Tujuannya adalah untuk menyadarkan saya, bahwa mereka (para pendukung Persija) tidak peduli dengan pencapaian-pencapaian pribadi saya. Berapa pun banyaknya gelar pribadi yang diperoleh seorang pemain, tak akan membuat para pendukung sebuah kesebelasan bergeming.
Yang meraka mau hanyalah gelar untuk klub, karena itulah yang akan menjadi kebanggan mereka. Gelar juara adalah satu-satunya imbalan setimpal, untuk loyalitas dan pengorbanan mereka dalam mendukung tim yang mereka cintai.
Setiap hari setelah malam itu, saya selalu terprovokasi setiap melihat piala plastik itu di ruang keluarga saya. Kejadian tidak mengenakkan di stadion, saat saya menerima piala itu seketika kembali terbayang. Timbul amarah dan rasa ingin membuktikan dalam diri saya. Membuktikan kepada mereka yang selama ini telah meremehkan kami, lebih utama lagi membuktikan kepada diri sendiri, bahwa saya (kami) lebih baik dari apa yang kami tampilkan saat ini.
Itu lah tujuan saya membawa piala plastik itu pulang. Agar kenyamanan saya terganggu. Agar saya tidak terlena dan berpuas diri. Agar timbul pemberontakan dari dalam diri saya. Dan agar saya memiliki tujuan yang jelas, untuk apa saya pergi berlatih setiap hari.
Pada pertandingan berikutnya, tanggal 2 Juni 2017, melawan Arema, Stadion Patriot Candrabhaga. Sebelum kick-off (di tengah lapangan) saya berbicara kepada para pemain. Sambil menatap sepuluh pasang mata yang lain, saya berkata:
"Kecintaan kita terhadap klub ini tidak sama, namun kecintaan kita terhadap sepak bola dan keluarga, saya pikir sama. Jadi jangan bermain untuk Persija Jakarta, tapi bermainlah untuk diri kalian, anak, istri, pacar, dan orang tua kalian. Ketika kita bermain untuk orang-orang yang kita cintai, maka hal-hal baik akan datang”.
Dan setelah dalam beberapa pertandingan terakhir kami tidak mampu menang. Malam itu, dalam sebuah pertandingan yang jauh dari kata mudah, akhirnya kami pun kembali berhasil mendapatkan poin maksimal. Kemenangan malam itu, menjadi momentum kebangkitan bagi kami untuk perlahan-lahan merangkak menaiki tangga liga. Belum stabil memang, tapi setidaknya kami sudah mulai berjalan menuju ke arah yang tepat.
Perjuangan pun berlanjut. Dalam perjalanannya beberapa kali kami sempat terjatuh, namun kami selalu mampu bangkit dan kembali berlari walau perlahan. Tekanan dari para pendukung kami pun masih cukup besar. Namun seiring membaiknya penampilan kami, tekanan tersebut pun perlahan-lahan mulai berkurang.
Hingga akhirnya, pada tanggal 9 Desember 2018, penantian sepanjang 17 tahun itu pun berakhir. Macan Kemayoran kembali berhasil menjadi yang terbaik di Indonesia. Kami berhasil bangkit dari keterpurukan, dan memberikan gelar ke sebelas bagi Persija Jakarta. Menjadi tim dengan koleksi gelar juara liga terbanyak di Indonesia.
Seperti yang sering saya sampaikan, bahwa motivator terbaik dalam hidup adalah diri sendiri. Bukan orang lain, siapapun itu. Namun demikian, untuk dapat memotivasi diri terkadang kita memerlukan orang lain, atau sebuah kejadian yang bisa jadi tidak menyenangkan. Namun dengan kejadian tersebut kita merasa tertantang dan ingin membuktikan, jika kita adalah orang-orang yang lebih baik dari yang mereka pikirkan.
Pada cerita di atas, saya menggunakan momentum kekecewaan suporter yang memberikan piala plastik bertulis “Persija Kapan Juara?”, untuk memprovokasi dan membuat saya marah, hingga akhirnya saya termotivasi untuk membuktikan diri.
Sepanjang karir saya, memang tidak semua pertempuran dapat saya menangkan. Tidak jarang saya pun tersungkur dan bersimbah darah. Namun demikian, setidaknya saya selalu dapat mengeluarkan kemampuan terbaik saya, untuk coba memenangkannya. Dan oleh karena itu tidak pernah ada penyesalan di sana.
Alih-alih untuk berdebat dengan para pengkritik, saya memilih untuk menyerap setiap kritik yang datang dan menjadikannya sebagai bahan bakar (motivasi) untuk menjadikan diri saya lebih baik. Karena ketika kita terlalu sibuk berdebat, maka kita kehilangan waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah (memperbaiki diri) kita.
“Berdebat hanya membuat kita mencari pembenaran, kembali bekerja dan memperbaiki apa yang kurang akan membuktikan siapa yang benar”.
26 Mei 2017, saya memposting piala plastik bertulis “Persija Kapan Juara?” dengan judul: “Rasa cinta memang dapat diwujudkan dengan cara yang begitu beragam”. 9 Desember 2018, saya memposting foto saya mengangkat piala liga Indonesia menghadap tribun penonton, dan saya beri judul: “Jakarta, This Is For You”.
Itu adalah jawaban saya (kami) atas kritik mereka.
Kewajiban pun terbayar lunas, tantangan terselesaikan, dan sebuah janji telah tertunai dengan baik. Setelah sembilan belas bulan terprovokasi oleh sebuah piala plastik, akhirnya beban berat di pundak saya pun berhasil saya lepaskan. Saya berhasil memenangkan pertempuran saya, sekali lagi.
Bukan pertempuran untuk mengalahkan orang lain, namun lebih kepada bagaimana saya mampu mengalahkan diri saya sendiri. Bagaimana saya mengendalikan kegelisahan, ego, dan amarah kemudian mengubahnya menjadi sebuah energi positif untuk mencapai sesuatu.
Karena sebelum kita mengalahkan orang lain dan mencapai sesuatu, kita harus terlebih dahulu mengalahkan diri sendiri.
PS: Sejak tanggal 10 Desember 2018, akhirnya saya pun berhasil memindahkan piala plastik bertulis “Persija Kapan Juara?” tersebut dari ruang keluarga saya. Saat ini piala tersebut berada di dalam gudang di rumah saya.
Selesai…..