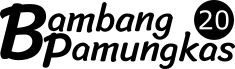Dahulu ketika ditanya oleh siapa pun mengenai bagaimana pandangan saya mengenai sepak bola di Indonesia, saya selalu menjawab:
“Di Indonesia sepak bola sudah menjadi sebuah profesi, di mana para pemain dibayar untuk memainkannya, dan membuat orang harus membayar untuk menyaksikannya.”
Hal tersebut tentu berkaitan dengan industri sepak bola, yang sudah dapat dijadikan sebagai sandaran hidup bagi para pelaku atau atletnya. Namun, seiring berjalannya waktu jawaban saya tersebut tampaknya sudah tidak lagi relevan, terutama dalam dua tahun terakhir. Hal tersebut berkaitan dengan begitu banyaknya kasus tunggakan gaji, yang dialami para pesepak bola profesional di Indonesia.
Hal yang paling baru adalah adanya gerakan dari para pemain PSMS Medan. Yang dalam hal ini nekat berangkat ke ibu kota untuk menemui pihak-pihak berwenang, guna mencari kejelasan mengenai hak-hak mereka yang tertunggak. Sebelas pemain tim Ayam Kinantan tersebut rela bermalam di pelataran monumen nasional, sebuah masjid di kawasan Gelora Bung Karno, serta makan seadanya dalam perjuangan mereka di Jakarta.
Dari 10 bulan durasi kontrak yang mereka tanda tangani, sampai dengan berakhirnya kompetisi, menejemen baru membayar sebesar setengah bulan saja. Oleh karena itu, mereka ingin bertemu dengan PT Liga Indonesia, PSSI, dan juga Menpora, dengan harapan dapat membantu mencari jalan keluar bagi permasalahan yang mereka alami. Bahkan mereka berniat untuk tinggal di depan kantor PSSI, sampai dengan adanya kejelasan mengenai permasalahan tersebut
Jika kita mau jujur, maka sejatinya PSMS Medan bukanlah satu-satunya tim yang mengalami permasalahan ini, dalam hal ini menunggak gaji pemain. Hampir 60% dari kontestan yang berlaga di kompetisi negeri ini, melakukan hal yang sama. Tidak terpenuhinya hak-hak dasar para pemain ini, terjadi di semua strata kompetisi di negeri ini.
Para pengurus akan melakukan apa pun untuk membuat pemain tetap bermain. Mulai dari bujukan, rayuan, janji-janji manis yang palsu, hinggalah intimidasi. Hal yang paling ampuh biasanya adalah intimidasi emosional sejarah. Intimidasi seperti ini biasanya akan membenturkan pemain dengan apa itu loyalitas, totalisan, pengorbanan, kebanggaan, harga diri, serta sejarah kebesaran sebuah klub.
Kalimat kurang lebihnya adalah: “Dahulu pemain-pemain seperti si A atau si B (legenda) berjuang mati-matian dengan bangga menjaga marwah dan harga diri klub ini, mereka rela mengorbankan apa pun. Sedang kalian baru begini saja (tidak digaji) sudah mengeluh, di mana loyalitas kalian kepada klub dan suporter kita. Bermain untuk tim sebesar ini, seharusnya sudah menjadi sebuah kebanggaan”.
Apakah ini menjadi hal yang wajar serta adil, ketika para pemain dituntut untuk berjuang menjaga harkat dan martabat klub dan daerahnya, tetapi hak-hak dasar mereka tidak diberikan? Para penonton yang bersorak menyemangati dari tribun itu, mungkin tidak sadar bahwa para pemain yang berjuang dan berjibaku menjaga harkat dan martabat tim kebanggan mereka, sejatinya tengah gamang.
Gamang karena hak mereka selama berbulan-bulan, tidak dibayarkan. Mereka resah karena di belakang mereka, terdapat banyak sekali permasalahan kehidupan yang belum terselesaikan. Satu-satunya hal yang masih membuat mereka tetap bermain, hanyalah kecintaan mereka terhadap sepak bola itu sendiri.
Banyak orang bersimpati, namun tidak sedikit yang berkomentar dengan nada sumbang. Salah satu di antaranya: “Sepak bola itu sebuah olahraga, sebuah kegiatan yang dilakukan berdasarkan hobi untuk bersenang-senang. Oleh karena itu uang hanya sebagai bonus, jadi tidak perlu dipikirkan. Itulah mengapa sepak bola Indonesia tidak maju-maju, karena yang ada di kepala pemain hanyalah uang, uang, dan uang.”
Mari kita kupas permasalah ini dengan sedikit lebih mendalam. Mengapa saya sebutkan jika sepak bola itu sebuah profesi? Karena dalam menjalankannya, para pemain terikat dengan kewajiban-kewajiban yang tertera di dalam klausul kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik klub dan pemain.
Beberapa di antaranya adalah berlatih baik pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan kebijaksanaan klub. Bermain dalam kompetisi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh federasi. Serta harus hadir dalam segala pertemuan atau kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh klub yang bersangkutan.
Artinya, waktu keseharian pemain hampir semua tersita, untuk segala hal yang berkaitan dengan kepentingan klub. Pemain tidak berhak melakukan pekerjaan lain yang sekiranya dapat mengganggu, atau berbenturan dengan kegiatan klub. Para pemain tersebut mencurahkan semua energi dan konsentrasi mereka, hanya untuk pekerjaannya sebagai pesepak bola, dan tidak memiliki pekerjaan sampingan yang lain.
Berbeda dengan sepak bola hanya untuk kesenangan dan kepuasan pribadi semata. Jika itu pembahasannya, maka kita akan kembali ke saat di mana para pesepak bola tersebut masih kecil. Ketika sepak bola dimainkan di lapangan-lapangan berlumpur, di jalan-jalan dan di bawah guyuran hujan. Ketika itu tidak ada aturan apa pun yang mengikat para pemain dengan pihak mana pun. Pemain boleh datang dan pergi kapan saja.
Kemenangan bukan menjadi sebuah tujuan, yang ada hanya kesenangan. Tidak ada tekanan dari pelatih dan menejemen, karena memang tidak ada pelatih dan menejemen. Tidak ada juga tekanan dari penonton, karena mereka datang tanpa dipungut bayaran. Siapa pun yang mencetak gol dan menang, penonton akan bersorak gembira.
Saat para pemain tersebut masih kecil, mereka tidak memiliki beban yang menggelayut di pundak mereka. Beban dalam hal ini adalah kewajiban atau tanggung jawab untuk memberikan nafkah. Sedang ketika para pemain tersebut menjadi dewasa dan menikah, maka dengan sendirinya mereka memiliki anak, istri, atau orang tua yang harus dinafkahi.
Oleh karena itu jika kita samakan pola pikir antara pesepak bola cilik, dengan pesepak bola dewasa mengenai apa arti sepak bola bagi mereka, maka pada hemat saya kita telah salah kaprah. Orientasinya jelas lain, tekanannya lain, dan ekpektasinya pun juga lain.
Sehingga ketika para pesepak bola profesional di negeri ini memperjuangkan hak-hak mereka, dan ada pihak-pihak yang mencibir atau bahkan menertawakan. Maka ada baiknya jika Anda kembalikan permasalahan tersebut kepada diri anda sendiri. Seandainya anda bekerja berbulan-bulan dengan tanpa mendapatkan upah, apakah Anda sekalian akan diam saja? Sedang di belakang Anda ada banyak kebutuhan yang harus diselesaikan. Toh yang mereka perjuangkan adalah hak dasar mereka berupa gaji, bukan beserta dengan bonus, atau malah bunga dari tunggakannya.
Alangkah bijaksananya jika kita mampu bersikap lebih arif dalam melihat, menyikapi, serta mengomentari permasalahan keterlambatan gaji pemain ini. Karena segala permasalahan ini telah membuat para pesepak bola yang bermain di negeri ini (baik lokal maupun asing) terlantar, jatuh sakit, dideportasi, hinggalah meninggal. Permasalahan ini sudah bukan lagi menjadi permasalahan sepak bola saudara-saudara, tetapi sudah menjadi sebuah isu kemanusiaan.
BOPI, PT Liga Indonesia, dan PSSI selalu berkata: ”Bermainlah dahulu, karena dengan liga tetap berjalan maka klub akan mendapatkan pemasukan, dan dengan pemasukan tersebut klub akan dapat melunasi hak-hak para pemain.”Teorinya memang demikian, namun fakta di lapangan berkata lain. Jangankan untuk melunasi tunggakan musim sebelumnya, musim yang saat ini tengah berjalan pun banyak tim yang tetap tidak mampu membayar gaji.
Mereka mampu menggulirkan liga, menghambur-hamburkan uang untuk memelihara konflik, hingga menjalankan konggres berulang-ulang. Hal tersebut tentu memakan dana yang tidak sedikit. Namun di sisi lain, mereka tidak mampu membayar gaji para pemain.
Tidakkah pihak-pihak yang bertanggung jawab itu, tersentuh dengan segala akibat dari permasalahan berkepanjangan ini? Apakah harus menunggu hingga ada nyawa lagi yang melayang, seperti apa yang dialami oleh Diego Mendieta?
Oleh karena itu di akhir artikel ini, perkenankan saya untuk sedikit mengubah testimoni saya mengenai sepak bola di Indonesia pada awal artikel ini, dengan kalimat sebagai berikut:
“Sepak bola adalah sebuah profesi, di mana para pemain dibayar untuk memainkannya, dan membuat orang harus membayar untuk menyaksikannya. Namun di Indonesia? Tidak lagi.”
Sekian….